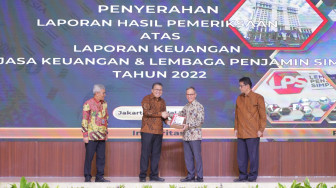1. Politik Hukum Ketika Kekuasaan Mengatur Hukum
Menurut Satjipto Rahardjo (2006), hukum tidak pernah berdiri sendiri di ruang kosong, melainkan selalu berada dalam pengaruh kekuasaan dan dinamika sosial. Hukum dapat menjadi instrumen pembebasan jika diarahkan pada keadilan, namun juga bisa berubah menjadi sarana penindasan ketika dikuasai oleh kepentingan politik tertentu.[8] Pada kenyataannya politik hukum di Indonesia kerap kali berjalan seiring dengan kepentingan pihak yang sedang berkuasa. Ketika era Orde Lama, hukum dijadikan instrumen untuk mewujudkan revolusi. Sementara di masa Orde Baru, hukum difungsikan sebagai alat menjaga stabilitas nasional. Memasuki era reformasi, muncul optimisme bahwa hukum akan lebih berpihak pada demokrasi, namun praktik oligarki dan kepentingan ekonomi-politik tetap membayangi proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
Fenomena judicial capture, yakni penguasaan lembaga peradilan oleh elit politik atau ekonomi menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kekuasaan terhadap jalannya penegakan hukum. Hal ini juga terlihat dalam penyusunan undang-undang yang lebih menguntungkan kelompok tertentu, seperti dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak menuai kritik karena dinilai mengabaikan prinsip keadilan sosial dan aspirasi publik.
2. Keadilan Hukum yang Terkungkung oleh Kepentingan
Secara ideal, sistem hukum harus berlandaskan pada prinsip rule of law, di mana seluruh warga negara, termasuk penguasa, berada di bawah supremasi hukum. Namun, kenyataannya di Indonesia, yang sering terjadi justru rule by law hukum dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Praktik ini terlihat jelas dalam proses legislasi yang minim partisipasi publik. Banyak undang-undang disahkan dengan terburu-buru tanpa pelibatan masyarakat secara substansial, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih berpihak pada kepentingan ekonomi segelintir orang daripada melindungi hak-hak rakyat.
Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, campur tangan politik serta lemahnya kemandirian lembaga peradilan menjadi persoalan mendasar yang menghambat tercapainya keadilan. Seorang hakim dalam perkara pidana kerap berada pada posisi dilematis antara menjunjung tinggi keadilan substantif dan menghadapi tekanan eksternal yang dapat mengikis independensi kekuasaan.[9] Selain itu, munculnya praktik mafia peradilan serta tindakan korupsi semakin memperburuk citra lembaga hukum di mata publik, menjadikan distribusi keadilan yang merata sulit untuk diwujudkan.[10]
3. Membangun Politik Hukum yang Berkeadilan
Mahfud MD (2010), menegaskan bahwa politik hukum yang ideal adalah politik hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima, bukan sebagai alat kekuasaan.[11] Dengan demikian, hukum seharusnya menjadi pedoman moral dan konstitusional yang menuntun arah kebijakan negara. Supaya mewujudkan politik hukum yang berkeadilan, diperlukan reorientasi paradigma hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi, peningkatan transparansi serta partisipasi publik dalam proses legislasi oleh DPR dan pemerintah, serta penegakan independensi lembaga peradilan sebagai benteng terakhir keadilan dari intervensi kekuasaan politik.
Baca Juga: Karhutla Dan Pentingnya Pemanfaatan Data Tinggi Muka Air Tanah
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS